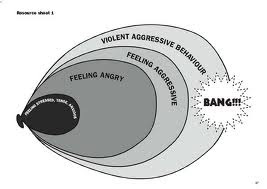*) Catatan, bagi yg belum siap, jangan baca ya. Oh ya, setelah pulih, Ken Steele menjadi aktivis kesehatan jiwa.
Jakarta, Senin Inilah "sisi dalam” seorang penderita skizofrenia. Hidupnya dikuasai “para iblis” di dalam kepalanya yang selalu menyuruhnya bunuh diri.
The Day the Voices Stopped: A Memoir of Madness and Hope (Mereka Bilang Aku Gila: Memoar Seorang Skizofrenik), yang dialihbahasakan oleh Rahmani Astuti dan diterbitkan oleh Qanita, Bandung, ini memaparkan pergulatan pengalaman pribadi penulisnya.
Suara-suara itu datang tanpa peringatan pada suatu malam bulan Oktober, saat aku berumur 14 tahun. “Bunuh dirimu - Bakar tubuhmu,” kata mereka. Beberapa menit sebelumnya, aku mendengarkan kelompok musik Frankie Valli and the Four Seasons, dari sebuah radio di samping tempat tidurku.
Suara-suara itu bernada rendah dan mendesak, mengejek, dan menertawakan, terus berbicara kepadaku dari radio. “Gantung dirimu. Dunia akan menjadi lebih baik tanpamu. Tak ada yang baik padamu, tak ada kebaikan sama sekali.”
Setiap kali aku berada di dekat pesawat televisi atau radio, suara-suara itu menjadi semakin keras dan kuat, dan tampaknya semakin banyak jumlahnya. Mereka seakan-akan sedang menulis dan menyutradarai kisah hidupku, menyuruhku melakukan apa yang boleh dan tidak boleh kulakukan.
Ketika ayahku bertanya tentang apa yang kami lihat di televisi, apa yang kuketahui, bagaimana pendapatku, aku melakukan apa yang diperintahkan suara-suara itu: meletakkan kedua tangan menutupi telingaku dan berbalik memunggungi dia.
Ayah marah besar. Lalu apa yang dikatakari suara-suara itu? “Anak tak tahu terima kasih, lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu telah mengecewakan ayahmu. Orangtuamu layak mendapatkan anak yang lebih baik daripada kamu."
Lalu, ketika Ibu dan Ayah memberitahuku bahwa mereka sedang menantikan seorang bayi, suara-suara itu lebih tahu. Mereka telah memastikan bayi itu laki-laki. Mereka membuat seakan-akan bayi itu bicara denganku. “Aku akan datang. Aku akan lahir,” calon adikku berbisik dengan bengis dari dalam perut ibuku yang membesar. “Kamu harus pergi!”
Aku juga didatangi bayangan-bayangan aneh: bentuk-bentuk tidak jelas yang bergerak di depan mata pikiranku. Terkadang, bayangan-bayangan itu muncul lebih jelas, tapi hanya selama beberapa detik. Bayangan-bayangan visual datang dan pergi, tapi suara-suara itu selalu menemaniku - kadang meraung di telingaku, kadang berceloteh di latar belakang. Semakin lama aku semakin cenderung mematuhi perintah-perintah mereka.
“Oke, aku akan membakar diri ... Aku akan gantung diri. Ya, ya, aku akan bunuh diri.” Saat itu bulan Agustus. Setelah aku mendengar ibuku menjerit dan ayahku mengguncang-guncang tubuhku, barulah aku sadar bahwa aku telah memuntahkan kata-kata itu di ruang keluarga di depan seluruh keluargaku.
Aku pun lari dari rumah. Aku lari ke hutan. Malam itu, aku melakukan tiga percobaan untuk mengakhiri hidupku. Pertama, aku berdiri di atas kursi, lalu mengikat tali itu ke leherku. Namun, aku tak berhasil menendang kursi itu supaya jatuh. Aku gagal. Aku turun dari kursi. Dengan air mata bercucuran di wajah, aku mencari cairan bahan bakar dan menuangkannya ke kepalaku. Aku tak sanggup menyalakan korek dan membakar diriku.
Suara utusan iblis
* Setengah berlari, dalam kebingungan aku menyeret tubuhku sepanjang satu mil menuju Rute 69, sebuah jalan padat lalu lintas. Rencanaku, melompat ke depan sebuah mobil. Aku berdiri di sisi jalan. Namun, aku melihat lampu sorot di atas mobil.
Bagaimana jika itu mobil polisi? Bagaimana jika polisi itu datang untuk menahanku? Dengan panik aku berlari kembali dari jalan.
Besok malamnya orangtuaku mengajakku menemui Dr. Sullivan. Setelah berbicara denganku, dokter itu bicara dengan Ayah. Wajah Ayah berubah. Setiba di rumah, aku bertanya pada Ayah tentang penyakitku. Ayah memberi selembar kertas, bertuliskan: “Skizofrenia”.
Pukul 10.00 keesokan harinya, aku sudah berada di perpustakaan, mencari arti kata itu di kamus kedokteran. Ternyata, penyakit jiwa! Suara-suara itu membesarkan volumenya dan mengejekku. “Ibu dan ayahmu ingin kamu lenyap dari kehidupan mereka.” Pelan-pelan aku mulai mempercayai pesan suara itu bahwa setiap orang di rumah menginginkan aku pergi - setiap orang. Kecuali nenek.
Suatu sore di bulan Agustus, nenek sedang duduk menjahit. Dengan tergagap karena takut dan malu, kuceritakan kepada nenek tentang suara-suara itu. Nenek menatapku tajam. Dari nenek kutahu, suara-suara itu utusan iblis, yang diperintah untuk menyikaku. Aku menyatakan perang melawan mereka.
Namun, aku harus mencari tempat berlindung. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke gereja Katolik Roma di Waterbury. Saat misa, suara pastur diikuti oleh suara-suara yang ada di kepalaku. “Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Kenny mengira bisa terbebas dari kami.” Mereka mengejek. “Kamu tak akan pernah terbebas dari kami. Tak ada ampunan,” kata satu suara. “Tak ada pembebasan,” tambah yang lain. “Tak ada keringanan atas dosa-dosamu,” tegas suara ketiga.
Tiba-tiba jemaat gereja membengkak jumlahnya, semua menatapku dengan pandangan menghina, marah, dan benci. “Musuhmu ada di mana-mana di sekelilingmu. Mereka tahu kamu dikutuk di neraka. Pergilah, lakuhan perintah mereka. Mati.” Sambil terhuyung-huyung aku lari meninggalkan gereja.
Menurut keyakinan umum, skizofrenia merupakan penyakit yang diturunkan dalam keluarga. Ketika aku bertanya apakah ada saudara ibu yang mengidap penyakit mental, ibu ingat ada seorang bibi dari generasi nenek buyut yang “terus menerus berbicara dengan Yesus”.
Tidak peduli apa pun alasannya, aku sudah hancur berkeping-keping di mata semua orang. Sebelumnya, aku murid teladan. Kini aku mulai gagal dalam pelajaran, sering membolos, dan malah pergi ke mana pun yang diperintahkan suara-suara itu.
Dibayangi suara
* Kini aku mengerti, perubahan yang berarti dalam nilai pelajaran dari sangat baik menjadi sangat buruk - merupakan tanda awal seorang anak sedang menghadapi kesulitan. Juga, mengasingkan diri merupakan salah satu gejala paling umum dari penyakit ini, dan keluarga harus memperhatikan hal itu.
Aku memang tak punya alasan untuk meninggalkan kamarku. Dalam kepalaku ada bermacam ragam karakter yang membuatku sangat sibuk.
Pada tahun-tahun awal penyakit itu aku masih dapat bolak-balik di antara dua duniaku. Namun, aku terjerembap semakin dalam ke “neraka”, tempat suara-suara itu mengambil alih kekuasaan atas diriku. Selama lebih dari setahun, aku ketakutan pergi ke luar untuk sekadar mengambil surat karena paranoiaku. Jantungku akan berdegup kencang dan keringat mengucur di wajahku saat memikirkan bahwa aku harus berjalan keluar pintu depan. Aku akan mengintip dari balik tirai kamarku, dengan obsesif mengawasi mobil-mobil dan orang-orang yang lewat.
Bagiku, ayah adalah setan paling besar. Hubungan kami telah memburuk sampai pada titik saat kami tidak bisa berada di satu ruangan atau di bawah atap yang sama. Aku takut dia akan memergokiku berbicara dengan suara-suaraku, yang terjadi semakin sering.
Membaca dan menulis tetap menjadi aktivitas satu-satunya dalam hidupku yang dapat membebaskanku dari suara-suara itu. Jika kupusatkan perhatian pada cerita yang kubaca atau entri-entri yang kutulis dalam buku harianku, konsentrasi itu akan menurunkan volume suara-suara itu dan sekali-sekali bahkan dapat membungkam mereka.
Usiaku 17 tahun, usia yang sudah mencukupi bagi seorang pemuda - dan orang yang tidak bersekolah - untuk diharapkan mendapat pekerjaan dan punya nafkah sendiri. Ayah sudah memperingatkan, “Saat kamu berumur 18 tahun, semua kewajiban ibumu dan aku atas dirimu sudah berakhir.”
Akhirnya, aku merantau ke New York, tinggal di apartemen kumuh, sendirian. Aku diterima bekerja sebagai pesuruh di penerbit Women’s Wear Daily. Setiap hari Sabtu, aku menenggelamkan diri di New York Public Library. Namun, buku dan pekerjaanku tak memberi perlindungan bagiku. “Pergilah berjalan-jalan, Kenny. Carilah bangunan yang tepat untuk melompat. Kamu punya waktu dan kesempatan.” Suara-suara itu terus menguntitku.
Aku berkenalan dengan Ted, pemuda rapi dan baik hati, yang sering mentraktirku makan siang. Aku merasa aman bersamanya. Setidaknya, aku tidak sendirian lagi.
Mengejutkan, sekitar dua bulan bekerja, aku ditawari posisi sebagai asisten redaksi di Majalah Men’s Wear, terbitan Fairchild lainnya. Selain bertugas menulis, aku juga membantu redaktur pelaksana soal mesin dan tata letak.
Celaka, suara-suara itu datang lagi. “Kamu tak bisa hanya duduk dan pura-pura sibuk. Mereka berharap kau menangani sesuatu, dan kamu tak akan mampu melakukannya.” Maka, pikiranku berkeliaran ke dunia suara-suara selama beberapa jam setiap hari, sementara tubuhku tetap di depan mejaku. Tiba-tiba, redaktur pelaksana berdiri di depanku, “Kau belum menyelesaikan pekerjaan itu?” Ia mengambil bahan tulisan di tanganku, “Kau jelas-jelas belum mengoreksinya dengan teliti!”
Aku semakin sering berbuat kesalahan, semakin sering diperingatkan, tapi siksaan mental itu mencegahku mempedulikan peringatan itu. Ada kekuatan besar mempengaruhi hidupku. Hanya enam bulan aku berhasil bertahan di dunia kerja yang nyata. Aku diberhentikan.
Terperosok jadi pelacur
* Akhir Agustus 1966, uangku tinggal beberapa dolar dan aku pasti diusir dari kamarku karena tak mampu membayar sewa. Ted menemuiku dalam tampang yang berantakan. Ia menyuruhku membersihkan tubuh, memakai celana jins putih ketat, dan menyisir rambutku.
Di sebuah kafe, ia mengenalkan pada Nick, yang menanyakan keadaan keuanganku. Ia langsung ke inti pembicaraan, “Sekarang kau bekerja untukku.” Lalu ia mengemukakan pengaturan untuk “mempekerjakan” aku, “Teddy akan memberi tempat tinggal, makan, dan pakaian padamu. Teddy yang akan memakaimu pertama kali, sebab dia yang merekrutmu. Aku akan memakai kamu kalau aku sedang ingin nanti. Akan ada para pelanggan - pria-pria lebih tua - yang menyukai anak-anak muda. Tugasmu membuat mereka senang. Semua janji dan pengaturan uang aku yang tangani. Kamu berikan setiap tip dan hadiah padaku, dan aku akan memberimu sebagian jika kupikir itu layak kau peroleh. Jelas?”
Selesai berhubungan seks dengan Ted di apartemennya, suara-suara itu datang lagi. “Bagai mana pendapat pendeta tentangmu sekarang? Apa kata nenek jika dia tahu apa yang dilakukan si kecil Kenny? Kau pelacur lelaki menjijikkan. Bocah busuk, kau benar-benar layak mati. Mati."
Benar, dengan sebagian dari diriku yang telah mati, masuklah aku ke dunia prostitusi pria. Menjadi pelacur seperti ini ada persamaannya dengan penderita skizofrenia: hal yang aneh dianggap normal. Aku menjadi kedua-duanya sekaligus.
Sebagai pendatang baru, aku sangat laris. Namun, sesudah berkencan dengan beberapa pelanggan, larut malam atau dini hari, aku kembali ke apartemen, dan Ted telah menungguku untuk mengambil “jatah”-nya. Melayani sekaligus semua lelaki, aku tak kuat lagi. Ted bilang, itu bagian dan kontrak kami. Ia lalu menyuruhku menemui Nick.
Hiii ... bos berwajah seram itu. Memasuki apartemen mewahnya, hatiku berdegup. Ia menungguku tanpa kemeja. Dada dan punggungnya penuh bulu, aku jijik. Berkilah mau membersihkan diri, aku langsung kabur. Memang, sebaiknya aku mengikuti saja perintah suara-suara itu. Lagi pula aku tak membayangkan jika Ted dan Nick serta para begundalnya bisa menemukan diriku. Lebih baik kurancang sendiri kematianku.
Aku sudah berada di tepi atap sebuah bangunan. Kakiku menggantung di sisinya, dan memandang ke bawah, mencoba menentukan titik paling tepat untuk menjatuhkan tubuhku di atas tanah. Hanya saja, dalam sekejap atap dipenuhi banyak sekali orang - polisi, petugas pemadam kebakaran, petugas ambulans, dan suara-suaraku. “Lihat semua orang itu. Mereka ke sini untuk mendorongmu jatuh jika kamu tak melakukannya sendiri. Pengecut. Lakukan sekarang.”
Seorang lelaki berjas dengan lembut membujukku, “Aku bisa membantumu. Ada obat yang membuat suara-suara dalam kepalamu pergi. Mari ikut aku.” Kubiarkan ia merengkuh tanganku. Tanpa disentuh oleh polisi, ia membawaku ke ambulans di bawah. Dalam keadaan dipegangi dan diikat ke tempat tidur, aku dibawa ke unit gawat darurat Manhattan State Hospital di Wars Island. Saat itu, Desember 1966, lebih empat tahun sejak suara-suara itu menggangguku.
Labirin psikotik
* Rumah gila. Kini aku berada di dalamnya. Suntikan obat penenang thorazin dosis tinggi membuatku lemah dan buta sementara. Aku terbaring selama dua bulan lebih, dan tak ingat apa pun.
Setelah kelopak mataku dibuka paksa dan bisa melihat kernbali, aku dibawa menghadap ke sidang para dokter dan hakim. Kata salah seorang, “Anda punya saudara selain keluarga dekat untuk bisa kami hubungi? Kami telah hubungi orangtua Anda, tapi mereka bilang, umur Anda sudah 18 tahun, dan hidup mandiri.”
Jantungku melesak. Aku telah didepak oleh orangtuaku! Tak ada seorang pun di atas bumi ini yang peduli denganku. Aku mulai bicara, tapi kata-kata itu tumpang tindih satu sama lain, terputar balik, tak dapat dimengerti. Apa yang terjadi padaku? Aku berjuang mengungkapkan satu pikiran, “Tolong. Aku tak tahu apa yang sedang menimpaku.” Namun, yang didengar dokter, aku hanya berceloteh.
Untunglah, di tengah komunitas yang mengerikan ini, masih ada perawat yang mau membawakan aku beberapa Majalah Reader’s Digest dan buku Catcher in the Rye. Tenggelamlah aku dalam bacaanku, terpisah dari dunia orang-orang gila itu.
Ketika aku mulai betah, dan memiliki seorang sahabat senasib, Anthony, suatu hari seseorang datang menjengukku ke rumah sakit. Ah, Teddy. Mengaku sebagai familiku, ia mengajakku kabur.
Setiba di apartemennya, Ted langsung membawaku ke tempat tidur. Setelah selesai, kutegaskan bahwa aku tak mau jadi pelacur lagi. Ted mengingatkan agar aku jangan main-main dengan Nick, “Dia mengharapkan kau kembali. Dia bahkan sudah mencatat daftar panjang untuk kencanmu.”
Setelah berbaur dengan pergaulan keras orang-orang sakit jiwa di rumah sakit, Nick bukan lagi sosok yang menakutkan bagiku. Dengan naik taksi aku kembali ke rumah sakit. Aku dikirim ke Harlem Valley State Hospital. Sayang, para stafnya tak terlalu suka membantu. Tak ada yang mau membawakanku buku. Atmosfer di sini amat berbau seks. Lebih dari sekali aku memergoki hal itu di kamar mandi.
Beberapa malam kemudian, dua orang pria memasuki kamarku. Aku kira mereka petugas. Mereka memerintahkanku untuk bangun. Mereka mengikat tanganku di belakang dan menutup mataku dengan kain kasar, lalu membawaku ke kamar mandi. Mereka membasahi dan menyabuni tubuhku. Aku tak bisa bergerak sama sekali. Mereka menyeretku ke kamar pengasinganku kembali. Lalu, mereka bergantian menindihku. Gelombang demi gelombang kesakitan yang semakin meningkat kurasakan di seluruh tubuhku. Suara-suara itu menyorakiku.
“Pelacur ... babi betina ... kamu cuma seonggok daging. Kamu jadi budak sekarang, pelayan semua pria. Kami menyuruhmu untuk mati. Gantunglah dirimu. Selesaikan ini, Kenny. Akhiri ceritanya di sini."
Aku dilarikan ke sebuah rumah sakit kecil di dekat Connecticut, menjalani pembedahan untuk memulihkan luka pada otot lingkar dubur akibat perkosaan itu. Lewat televisi yang dinyalakan perawat di kamarku, suara-suara itu datang lagi. Berbeda dengan sebelumnya, mereka mencurahkan perhatian pada kemarahanku. “Kamu harus membalas dendam, Kenny. Beri mereka pelajaran. Kami mencari cara supaya kamu bisa membalas dendam sampai tuntas.”
Setelah dirawat tiga minggu, aku dikembalikan ke Harlem Valley, ke ruang perawatan yang dihuni para manula. Beberapa menganggapku anak atau cucu mereka. Dua orang nenek menyatakan bahwa aku ayahnya. Yang lain percaya bahwa aku suaminya dan mencaciku karena tak mau menemaninya. Ada yang berkeras dialah presiden Amerika Serikat. Ada pula dua pria yang mengaku sebagai Musa. Dua orang lainnya menyatakan diri sebagai Yesus.
Beberapa bulan di sini, aku masuk daftar pembebasan. Anthony, sahabatku, dibebaskan lebih dulu. Setelah aku dan Anthony saling mengucapkan selamat tinggal, Tuan Marks, pekerja sosialku, berkata, “Jika kamu punya keluarga yang memintamu pulang, kesempatan dibebaskan jauh lebih besar. Tapi itu mustahil. Orangtuamu punya anak kecil dan mereka tak berani menanggung akibatnya.”
Ayah ibuku telah menghubungi rumah sakit, telah bercerita tentang adikku, malah telah mengirimiku uang. Namun, mereka tak pernah mengunjungiku, bahkan tak pernah meneleponku. Jika orangtuaku mau mendampingiku sejak awal dan mau mendukungku, mungkin akan berpengaruh baik pada penyakitku.
“Sudah kami bilang kalau ini akan terjadi. Bayi itu sendiri sudah memberitahumu, dulu sekali ketika ia masih ada di perut ibumu.” Suara-suara itu seperti mendapat kemenangan. Aku mulai lebih sering berpikir tentang bunuh diri. Aku bertanya-tanya, hidup seperti apa yang terbentang di depanku. Satu—satunya teman sejatiku, Anthony, sudah pergi, dan aku sudah dibuang keluargaku sendiri. Mungkin aku memang akan dibebaskan suatu hari tapi untuk apa? Aku belum pernah merasakan begitu sendirian sebelumnya.
Menemukan jati diri
* Hanya suara-suara itulah yang kumiliki. Mereka mendesakku untuk melarikan diri. Kadang-kadang aku melihat suara-suara itu. Penampakan itu nyata - dan mengerikan.
Si Penguasa, yang suaranya paling dominan, adalah iblis - bukan setan dengan wajah merah dan bertanduk, melainkan seekor makhluk serigala yang lebih besar daripada serigala betulan, berdiri tegak dengan dua kaki. Suara-suara lain, setan-setan yang lebih kecil, adalah sekawanan anjing, tapi juga manusia.
Mengikuti instruksi mereka, akhirnya aku melarikan diri ke Boston. Dua bulan aku berkeliaran di kota ini, tidur di emperan toko, membuat tempat tidur dari daun-daun kering di taman. Untuk makan, aku mengais-ngais kotak sampah di belakang restoran, bersyukur jika menemukan sisa makanan yang telah dibuang. Orang-orang menyisih saat aku lewat.
Ah, aku tertangkap lagi. Aku tetap membisu karena lelah berbicara. Akibatnya, aku dikirim ke Westboro State Hospital. Di sini aku mengganti identitas, bahkan namaku menjadi K. Shannon Steele. Dengan penuh pengertian, seorang perawat memperhatikan perubahan dalam diriku. Aku ditempatkan di rumah transisi, Kampus Westboro, tempat para pasien yang dianggap bisa hidup lebih mandiri.
Di sini aku menunjukkan bakatku sebagai koki kepala. Bahkan, aku diterima bekerja di suatu panti wreda. Inilah periode stabil bagiku. Saat-saat paling produktif, ketika aku berhasil membangun harga diri. Aku membutuhkan pekerjaan yang dapat memberi makna dan bukannya diberi tugas untuk sekadar membuatku sibuk.
Dua minggu bekerja di dapur panti wreda, aku dipanggil kepala perawat. Aku ditawari jadi asisten perawat. Kujalani tugas itu, yang selama delapan bulan mendekatkan aku pada kehidupan normal. Tiba-tiba, suatu malam aku mendapat kabar, perawat McCarthy yang telah berjasa padaku itu diserang pasien yang baru masuk. Bayi yang dikandung perawat itu lahir prematur, hanya bisa bertahan hidup tiga minggu.
Suara-suara itu langsung menyerangku. “Jika bukan karena kamu, perawat McCarthy tak akan kehilangan bayinya. Dia berencana cuti hamil, tapi kamu datang. Ada korban bayi lagi, kau tahu? Berapa banyak lagi orang yang akan kau sakiti? Kau harus mati supaya orang lain hidup. Kapan kau akan menjalankan perintah kami? Bunuh diri, itulah satu-satunya jawaban.”
Dilanda badai psikotik seperti itu, aku jadi jijik pada diri sendiri. Aku sudah berusaha keras meraih kehidupan yang berguna, tapi setiap usaha justru mendatangkan bencana dan aku kembali di tempatku semula: terkutuk berkelana di dunia sendirian.
Cepat kukemasi barang, lalu aku kembali ke jalanan. Tidur di toilet umum. Terpaksa menumpang trailer-traktor besar menuju Chicago, dengan imbalan “pelayanan seksual tertentu”. Dari sopir itu aku berkenalan dengan alkohol, yang ternyata membantuku meredakan suara-suara itu.
Melompat dari Golden Gate
* Aku terseret lagi masuk dunia gay, dan “ditemukan” seorang anak jutawan, Karl, yang membawaku pergi naik pesawat dan tinggal di hotel berbintang. Aku sangat terpukul ketika beberapa hari kemudian Karl ditemukan mati bunuh diri.
Kembali kususuri jalanan Kota Denver, meringkuk di emperan toko. Suara-suara itu menuntunku berjalan satu setengah hari menyusuri Highway 25, menunggu truk berukuran besar untuk melemparkan tubuhku di depannya. Sayang, polisi meringkusku, dan mengirimku ke Pueblo State Hospital di Pueblo, Colorado. Aku diasingkan dalam sebuah lemari besar. Amat tersiksa. Beruntunglah orangtuaku turut campur mengeluarkan aku dari “neraka” ini.
Setelah sepuluh tahun menghilang, akhirnya aku diterima kembali di rumah orangtuaku. Adikku Joey sudah besar. Hubungan kami kembali menghangat, meskipun ayah tetap terus mengawasiku. Aku diterima bekerja di pabrik di tengah Kota Waterbury. Di rumah, kami makan malam bersama. Sungguh keluarga bahagia.
Namun, ih ... suara-suara itu membujukku untuk meniru kematian seorang wanita muda, Karen Ann Quinlan, yang menemui ajal setelah meminum obat anticemas, valium dan librium, sekaligus. Perpaduan ini bisa menyebabkan mati otak. Ya, aku ingin membunuh otakku agar suara-suara itu tak mengganggu lagi.
Begitulah, suatu pagi di bar dekat pabrikku, aku menelan semuanya, dibantu alkohol. Tiba-tiba aku pingsan. Polisi memenjarakan aku. Ayah datang membayar uang jaminan. Aku boleh pulang. Esoknya, dengan amat marah ibu melemparkan koran Waterbury Republican ke wajahku. Di dalamnya tertulis, Kenneth Steele ditangkap dengan tuduhan: tindakan cabul, melawan penangkapan, perilaku mengacau, mengganggu ketenangan.
Aku terpaksa “membuang diri” kembali dari lingkungan keluarga. Apalagi Ayah berkata tegas, “Begitu urusanmu selesai, kuharap kau pergi dari sini dan tak pernah kembali lagi.” Kuputuskan masuk kembali ke rumah sakit jiwa, Norwich State Hospital di tenggara Connecticut. Dua tahun aku di sini. Berperilaku baik, lalu diterima di rumah transisi, dan menjadi asisten perawat di suatu panti wreda. Aku pun berjuang mengurangi kebiasaan merokok, dari tiga pak sehari menjadi hanya satu pak.
Aku mengumpulkan uang untuk satu tujuan baru. Apakah itu? Aku ingin terbebas dari suara suara itu, karenanya harus punya uang untuk naik bus dari Connecticut ke San Fransisco, menyisakan sedikit uang untuk makan dan sewa kamar setiba di sana. Sisa itu tak usah banyak-banyak. Toh, aku berniat bunuh diri dengan melompat dari Jembatan Golden Gate!
Matikah Ken Steele? Ternyata, dunia nyata selalu “menyelamatkan”-nya. Epimenides, peramal Kreta yang hidup pada abad ke-6 SM, berkata, “Ada kesenangan menjadi gila yang tak dapat dirasakan oleh orang lain kecuali orang gila.”
Ken merasakannya. “Suara-suara itu telah mengisi tempat khusus dalam hidupku. Tanpa mereka, aku merasa sendirian.” (Dharnoto/Intisari)